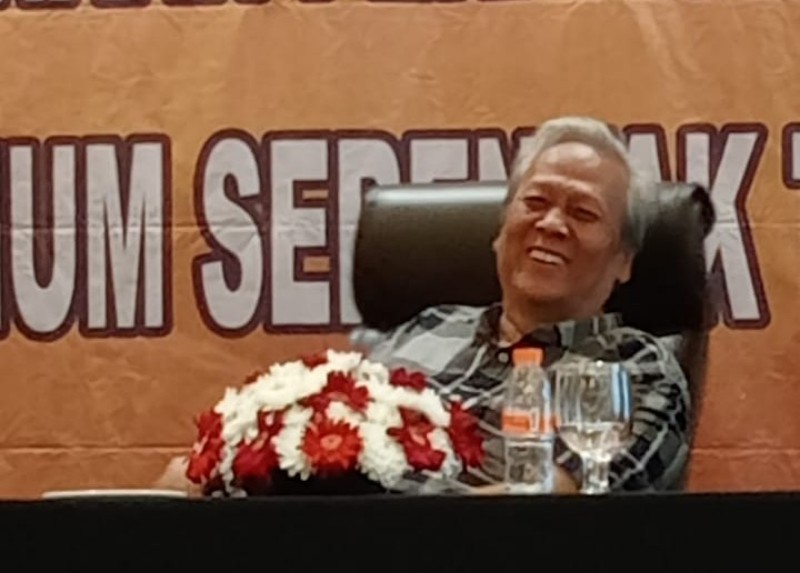
Achmad Fachrudin, Dosen Jurnalistik Universitas PTIQ. *Ist
Oleh: Achmad Fachrudin, Dosen Universitas PTIQ Jakarta
SETIAP kali umat Islam menyongsong kedatangan bulan suci Ramadhan termasuk pada tahun 2026/1447 H, selalu hadir suasana kebatinan tidak sederhana. Ramadhan seakan menggantungkan manusia beriman pada satu ruang psikologis yang penuh kompleksitas. Diantara rasionalitas yang menimbang makna ibadah, spiritualitas yang merindukan kedekatan dengan Tuhan dan intuisi moral yang peka terhadap realitas sosial. Kompleksitas ini sering kali menyeruak dalam ekspresi paradoks antara kegembiraan dan keprihatinan hadir bersamaan.
Namun, kompleksitas atau bahkan kontestasi psikologis semacam itu sejatinya bukanlah problem teologis yang harus dihindari karena senyatanya memang tidak bisa dihindari. Kondisi tersebut justeru merupakan tanda wajar yang semestinya dialami oleh seorang mukmin dan shā’im (orang yang berpuasa). Sebab bagi muslim otentik, Ramadhan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan “peristiwa eksistensial”: sebuah momentum yang memaksa manusia beriman untuk mengaudit dirinya sendiri, menimbang ulang arah hidupnya, sekaligus menegosiasikan ulang relasi vertikal kepada Allah dan relasi horizontal kepada sesama.
Bahkan, apabila seseorang menyambut Ramadhan tanpa mengalami sedikit pun pergulatan batin —tanpa rasa harap dan takut, tanpa rindu dan cemas, tanpa dorongan perubahan dan rasa malu atas kekurangan— maka justeru di situlah otentisitas dan genuinitas keberagamaannya patut dipertanyakan. Sebab dalam Islam, beragama tidak berhenti pada kesalehan individual yang bersifat privat, melainkan menuntut kesalehan sosial yang berdampak publik.
Dalam realitas praksis, menggabungkan dua bentuk kesalehan ini bukanlah pekerjaan ringan. Hanya sedikit yang mampu mewujudkannya secara komprehensif dan maksimal. Selebihnya, lebih banyak yang terjebak pada bentuk-bentuk kesalehan yang parsial, partikular, bahkan selektif. Serta kegiatan keagamaan ritualistik, dan tidak menyentuh pada dimensi substansialistik.
Horison Keagamaan
Jika merujuk pada horizon normatif ajaran Islam, baik Al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad SAW, Ramadhan digambarkan sebagai bulan yang memiliki kedudukan spiritual luar biasa. Ia bukan sekadar “bulan ibadah”, melainkan bulan yang dipenuhi pesan-pesan transendental tentang rahmat, pengampunan, pendidikan jiwa, dan kemuliaan manusia. Bahkan, teks-teks keagamaan memberikan “bonus-bonus pahala” yang tidak terukur secara rasional. Seolah ingin menegaskan bahwa Ramadhan adalah musim panen spiritual bagi siapapun yang masuk ke dalamnya dengan kesungguhan.
Al-Qur’an menggambarkan bahwa di dalam Ramadhan terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya melampaui seribu bulan (QS. Al-Qadr: 3). Dalam perspektif spiritual, ini bukan sekadar angka hiperbolik, melainkan penegasan bahwa ada dimensi waktu sakral yang dapat melampaui kalkulasi manusia. Ramadhan juga diposisikan sebagai bulan dikabulkannya doa dan kedekatan Allah kepada hamba-Nya (QS. Al-Baqarah: 186), sebuah ayat yang menempatkan hubungan Tuhan-manusia bukan dalam jarak metafisik yang kaku, melainkan dalam kedekatan yang penuh kasih.
Lebih dari itu, Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia (QS. Al-Baqarah: 185). Ini menunjukkan bahwa Ramadhan bukan hanya momentum ibadah fisik, tetapi juga momentum epistemik: bulan pembentukan kesadaran melalui wahyu. Puasa pun diposisikan sebagai tarbiyah (pendidikan) yang melatih takwa, kesabaran, dan disiplin (QS. Al-Baqarah: 183). Dengan kata lain, Ramadhan adalah institusi spiritual yang didesain wahyu untuk membangun manusia dari dalam.
Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas Al-Qur’an bahkan jauh lebih banyak menggambarkan keutamaan Ramadhan. Di dalam hadis, Ramadhan bukan hanya bulan kewajiban, tetapi bulan yang dipenuhi intervensi rahmat: pengampunan dosa, pembukaan pintu surga, penutupan pintu neraka dan pelepasan manusia dari jerat kebinasaan moral. Puasa disebut sebagai perisai (junnah), yakni benteng pelindung dari dosa dan api neraka. Bahkan, orang yang berpuasa dijanjikan pintu surga khusus bernama Ar-Rayyan.
Ramadhan juga disebut sebagai bulan dilipatgandakannya pahala. Gambaran ini seakan menegaskan bahwa Ramadhan adalah “rezim spiritual” yang berbeda: kualitas amal dalam bulan ini tidak dinilai secara linear, melainkan dengan logika ilahi yang melampaui ukuran manusia.
Di tengah banyaknya hadis yang populer dalam tradisi dakwah, terdapat pula ungkapan yang sering dikutip oleh para dai dan daiyah: “Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadhan, maka jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka.” (dinisbatkan kepada HR. an-Nasa’i). Pesan moral yang ingin ditegaskan hadis tersebut sangat jelas: kegembiraan terhadap Ramadhan adalah tanda keterhubungan batin seorang hamba dengan rahmat Tuhan.
Dipsaritas Keagamaan
Melalui legitimasi dalil-dalil naqli (Al-Qur’an dan hadis), umat Islam secara umum menyambut Ramadhan dengan kegembiraan dan suka cita, meskipun kadar spiritualitas dan religiusitas masing-masing tentu tidak seragam. Pada kelompok muslim yang memiliki kualitas iman yang memadai —bahkan sampai pada tingkat konsistensi (istiqāmah) dan fokus ibadah (khusyū’) —kegembiraan menyambut Ramadhan biasanya diwujudkan melalui pembaruan niat (tajdīd al-niyyah), pembersihan hati dan jiwa (tazkiyat al-qalb wan nafs), serta kesiapan melakukan “reset” orientasi hidup: dari kesibukan duniawi menuju kesibukan ukhrawi.
Pada titik ini, Ramadhan dipahami bukan hanya sebagai bulan menahan lapar, melainkan sebagai bulan menahan diri dari segala yang mengotori jiwa: dari kebiasaan menunda-nunda kebaikan, dari kelalaian moral, dari kerakusan konsumtif, hingga dari kesombongan sosial. Ramadhan menjadi semacam “ruang latihan” untuk memulihkan kemanusiaan.
Sebaliknya, bagi sebagian umat Islam yang kualitas keimanannya kurang memadai —termasuk kelompok yang oleh Clifford Geertz disebut sebagai abangan— ekspresi menyambut Ramadhan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk spiritualitas dan religiusitas yang kuat. Pada kelompok ini, Ramadhan sering tampil lebih dominan sebagai peristiwa sosial-budaya: tradisi keluarga, seremonial, dan aktivitas fisik yang bernuansa kebiasaan.
Sebagian muslim abangan tetap menjalankan puasa sebagai bentuk menggugurkan kewajiban, namun sebagian lainnya tidak melaksanakannya sama sekali. Kegiatan yang dilakukan lebih banyak berkisar pada ritual sosial seperti mengunjungi orang tua, ziarah kubur, membersihkan rumah, memperbaiki bangunan, atau melakukan persiapan-persiapan yang bersifat lahiriah. Aktivitas ini tidak sepenuhnya negatif, namun menunjukkan bahwa Ramadhan bagi sebagian orang lebih dipahami sebagai “musim tradisi”. Bukan musim transformasi spiritual.
Pada kategori religiusitas yang lebih jauh di bawah standar minimal, terdapat kelompok yang dapat disebut sebagai “agnostik praktis”. Mereka mungkin masih mengidentifikasi diri sebagai bagian dari penganut agama tertentu, namun tidak merasa perlu untuk melaksanakan perintah agama secara serius. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban puasa Ramadhan. Dalam spektrum ini, agama diposisikan sebagai identitas sosial semata, bukan komitmen etis.
Lebih ekstrem dari itu adalah kelompok yang berada pada posisi Islamofobia: suatu sikap ketakutan berlebihan terhadap Islam yang dapat bertransformasi menjadi antipati, sinisme, kebencian, bahkan pelecehan terhadap ajaran, simbol-simbol Islam, serta para penganutnya. Islamofobia sering tidak berhenti pada “perasaan”, tetapi bergerak menjadi tindakan sosial, termasuk perlawanan terhadap ekspresi publik umat Islam.
Dalam konteks Ramadhan, gejala ini kadang tampak ketika ada upaya dari sebagian kelompok muslim untuk mendorong pembatasan operasional tempat hiburan malam atau aktivitas yang dianggap mengganggu kekhusyu’an Ramadhan. Sebagian kelompok Islamofobik justru berada di garis terdepan untuk mengejek, menyindir, atau memproduksi narasi resistensi secara tajam. Mereka menganggap Ramadhan sebagai bentuk dominasi simbolik umat Islam di ruang publik, bukan sebagai momentum spiritual yang harus dihormati secara sosial.
Dimensi Sosial
Ekspresi kegembiraan dalam menyambut Ramadhan sejatinya tidak cukup berhenti pada euforia simbolik atau romantisme spiritual semata. Kegembiraan itu semestinya lahir secara lebih utuh: melalui kesadaran rasional (akal yang memahami makna puasa), kesadaran spiritual (hati yang tunduk kepada Allah), serta intuisi moral (rasa batin yang peka terhadap penderitaan sesama). Dari sini, kegembiraan Ramadhan diharapkan berbanding lurus dengan tumbuhnya kesadaran etis, kedisiplinan diri, dan kesalehan sosial.
Dalam konteks ini, Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim menegaskan bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan latihan pengendalian diri, proses penyucian jiwa, dan sarana menumbuhkan empati sosial. Puasa, dengan demikian, menuntut dua dimensi sekaligus: kesalehan ritual yang kuat dan kesalehan sosial yang nyata. Ibadah tidak hanya membentuk hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga memperhalus hubungan horizontal manusia dengan sesama.
Keharusan untuk berlaku etis dan membangun solidaritas sosial menemukan momentumnya pada realitas objektif Indonesia hari ini. Di tengah berbagai kemajuan, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Tidak sedikit pula yang menjalani hidup dalam tekanan berat akibat ketiadaan pekerjaan, penghasilan tidak menentu, serta beban ekonomi keluarga yang terus meningkat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Ramadhan tidak hanya menuntut kesalehan ritual, tetapi juga kepedulian sosial yang konkret. Sebab, kegembiraan spiritual akan terasa timpang bila tidak disertai kepekaan terhadap penderitaan sesama.
Gambaran itu terlihat pada pekerja informal perkotaan —buruh harian, tukang ojek, pedagang kecil, hingga pekerja serabutan— yang pendapatannya bergantung pada cuaca, pasar dan keberuntungan harian. Dalam situasi demikian, sahur dan berbuka dengan menu bergizi sering menjadi kemewahan; bahkan kebutuhan dasar seperti beras, listrik, dan biaya sekolah harus dihitung ketat.
Di pedesaan, banyak keluarga hidup dari pertanian kecil yang hasilnya minim, sementara harga kebutuhan pokok terus naik, sehingga mereka terpaksa berutang atau bergantung pada bantuan kerabat. Lebih memprihatinkan lagi, warga yang terdampak banjir dan longsor besar di sejumlah wilayah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh pada akhir 2025, hampir pasti menyongsong Ramadhan dengan beban hidup yang lebih berat.
Ajang Dialektika
Situasi tersebut menegaskan bahwa puasa tidak layak dipahami secara sempit dan individualistik. Sebab realitas sosial memperlihatkan kontras yang tajam: di satu sisi ada orang yang berbuka dengan meja penuh hidangan, sementara di sisi lain ada saudara-saudara kita yang bahkan tidak sepenuhnya yakin apakah hari itu mereka bisa makan dengan layak.
Kontras ini bukan sekadar pemandangan ekonomi, melainkan cermin moral yang menguji kejujuran spiritualitas kita. Ramadhan, dalam konteks ini, tidak hanya menghadirkan rasa lapar sebagai pengalaman pribadi, tetapi juga membuka mata nurani tentang adanya ketimpangan, kerentanan dan luka sosial yang masih menganga di sekitar kita.
Karena itu, puasa semestinya dimaknai sebagai ruang dialog —bahkan dialektika— antara rasionalitas dan spiritualitas: antara kegembiraan menyambut rahmat Allah dan keprihatinan atas derita sesama. Dari dialektika inilah puasa menemukan tujuan terdalamnya, yakni membentuk kesalehan yang utuh: kesalehan ritual yang menguatkan hubungan dengan Tuhan, sekaligus kesalehan sosial yang menghidupkan empati, solidaritas dan keberpihakan.
Jika dijalankan secara kolektif-kolegial, Ramadhan dapat menjadi momentum strategis untuk menjawab problem aktual bangsa —kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, bencana, hingga krisis moral— dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika, sehingga ibadah benar-benar menjelma menjadi energi transformasi sosial. *


